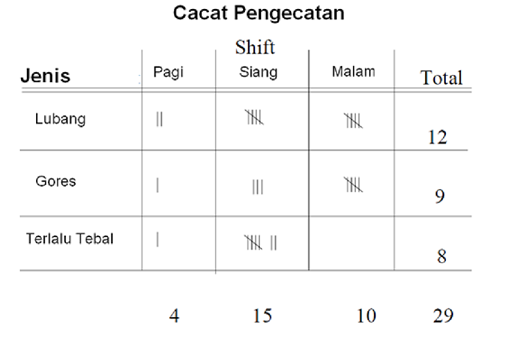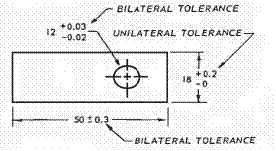Secara umum dikatakan bahwa pengukuran adalah membandingkan sesuatu
dengan besaran standar. Agar dapat digunakan, maka besaran standar
tersebut harus dapat didefinisikan secara fisik, tidak berubah karena
waktu, dan harus dapat digunakan sebagai alat pembanding di mana saja,
besaran standar tentunya memerlukan satuan-satuan dasar. Sistem metrik
digunakan oleh hampir seluruh negara-negara industri dimana satuan
dasarnya banyak mengikuti
international system of units atau SI
Units yang di dalamya dikenalkan bermacam-macam satuan dasar. Untuk
dapat melakukan pengukuran dengan bantuan satuan dasar tersebut
diperlukan alat ukur.
Konstruksi Umum dan Alat Ukur
Kita telah mengenal apa yang disebut dengan mistar atau penggaris,
mistar ini ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari pastik, dan yang
paling baik terbuat dari besi
stainless. Pada salah satu
penampang lebar dari mistar tersebut biasanya dicantumkan angka-angka
yang menunjukkan skala dari mistar. Dengan mistar ini kita dapat
menentukan ukuran panjang sesuatu yang besarnya dapat dibaca langsung
dari penunjukan skala yang ada pada mistar. Dengan mistar ini kita dapat
menentukan ukuran panjang sesuatu yang besarnya dapat dibaca langsung
dari penunjukan skala yang ada pada mistar. Dengan demikian mistar yang
digunakan untuk mengukur panjang tersebut dapat dinamakan sebagai alat
ukur. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa mistar merupakan alat ukur
yang paling sederhana bila ditinjau adanya satuan dasar.
Geometri benda ukur biasanya begitu komplek sehingga dalam pengukuran
diperlukan kombinasi cara dan bentuk pengukuran yang bermacam-macam.
Dengan demikian diperlukan juga bermacam-macam alat ukur yang memiliki
karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik dari alat-alat ukur inilah
yang menyebabkan adanya perbedaan antara alat ukur yang satu dengan alat
ukur lainnya. Karakteristik ini biasanya menyangkut pada konstruksi dan
cara kerjanya. Secara garis besar, sebuah alat ukur mempunyai tiga
komponen utama yaitu sensor, pengubah dan pencatat/penunjuk.
Alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari
suatu kuantitas atau variabel fisis. Pada umumnya alat ukur dasar
terbagi menjadi dua, yaitu alat ukur analog dan digital. Ada dua sistem
pengukuran yaitu sistem analog dan sistem digital. Alat ukur analog
memberikan hasil ukuran yang bernilai kontinu, misalnya penunjukkan
temperatur yang ditunjukkan oleh skala, petunjuk jarum pada skala meter,
atau penunjukan skala elektronik. Alat ukur digital memberikan hasil
pengukuran yang bernilai diskrit. Hasil pengukuran tegangan atau arus
dari meter digital merupakan sebuah nilai dengan jumlah digit tertentu
yang ditunjukkan pada panel display-nya.
Sensor atau Peraba
Sensor merupakan bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat ukur
dengan benda atau objek ukur. Atau dengan kata lain sensor merupakan
peraba dari alat ukur. Sebagai peraba dari alat ukur, maka sensor ini
akan kontak langsung dengan benda ukur. Contoh dari sensor ini antara
lain yaitu: kedua ujung dari mikrometer, kedua lengan jangka sorong,
ujung dari jam ukur, jarum dari alat ukur kekasaran. Contoh-contoh
sensor ini termasuk dalam kategori sensor mekanis. Pada alat-alat ukur
optik juga memiliki sensor yaitu pada sistem lensanya. Ada juga sensor
lain yaitu sensor pneumatis yang banyak terdapat dalam alat-alat ukur
yang prinsip kerjanya secara pneumatis.
Pengubah
Ada satu bagian dari alat ukur yang sangat penting yang berfungsi
sebagai penerus, pengubah atau pengolah semua isyarat yang diterima oleh
sensor, yaitu yang disebut dengan pengubah. Dengan adanya pengubah
inilah semua isyarat dari sensor diteruskan ke bagian lain yaitu
penunjuk/pencatat yang terlebih dahulu diubah datanya oleh bagian
pengubah. Dengan demikian pengubah ini mempunyai fungsi untuk
memperjelas dan memperbesar perbedaan yang kecil dari dimensi benda
ukur. Pada bagian pengubah inilah yang diterapkan bermacam-macam cara
kerja, mulai dari cara kinematis, optis, pneumatis, sampai pada cara
gabungan.
- Pengubah Mekanis
Cara kerja dari pengubah mekanis ini berdasarkan pada prinsip kinematis
yang melakukan perubahan gerakan lurus (translasi) menjadi gerakan
berputar (rotasi). Contohnya antara lain yaitu: sistem kerja roda gigi
dan poros bergigi dari jam ukur (dial indicator), sistem kerja ulir dari mikrometer.
- Eden-Rolt “Milionth” Comparator
Alat ini sangat cocok sekali untuk mengalibrasi blok ukur (gauge block)
karena bisa diperoleh perbesaran yang cukup tinggi. Hal ini terjadi
karena adanya kombinasi gerakan mekanis yang didukung dengan sistem
pengubah optis.
- Alat ukur pembanding Johanson mikrokator
Alat ini ditemukan oleh seorang insinyur bangsa Swedia yang kemudian
dibuat oleh pabrik C.E. Johanson Ltd. Oleh karena itu disebut dengan
nama Johanson Mikrokator. Pada bagian pengubah ini terdapat plat tipis
dan jarum penunjuk yang diletakkan ditengah-tengahnya. Dari
tengah-tengah ini plat tipis tersebut dipuntir dengan arah yang
berlawanan sehingga berbentuk spiral kiri dan spiral kanan. Salah satu
ujung plat tipis dipasang tetap pada batang pengatur, dan ujung yang
lain pada lengan penyiku dimana lengan penyiku ini dihubungkan dengan
batang pengukur. Dengan naik turunnya batang pengukur ini maka lengan
penyiku akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Dengan bergeraknya lengan
penyiku ini maka pelat tipis yang berbentuk spiral tadi juga akan
menjadi bertambah kuat atau bertambah lemah pilinannya. Bertambah kuat
atau lemahnya pilinan ini akan menyebabkan jarum penunjuk bergerak.
Perubahan gerak ini dapat dibaca pada skala, yang berarti juga perubahan
dimensi dari objek ukur. Perbesaran alat ini mencapai 5000 kali.
- Alat ukur pembanding Sigma Comparator
Alat ukur ini dibuat oleh Sigma Instrument Company. Bagian pengubah alat
ini menggunakan sistem engsel yang bebas gesekan. Sistem engsel ini
ditunjukkan oleh dua buah blok, blok tetap F dan blok bergerak M, yang
kedua-duanya dihubungkan oleh tiga plat tipis secara menyilang. Apabila
batang pengukur yang ada sensor pada ujungnya menyentuh objek ukur maka
batang ukur akan bergerak dan akan menggerakkan bagian penekan.
Bergeraknya bagian penekan ini akan menggerakkan blok M yang dihubungkan
oleh lengan Y ke bagian silinder penunjuk r yang pada bagian penunjuk
ini ada perantara pita tipis dari fosfor perunggu. Pada silinder
penunjuk juga ada jarum penunjuk R yang menunjukkan skala pengukuran.
Karena lengan Y bergerak akibat perubahan blok M maka silinder penunjuk
juga bergerak yang akibatnya jarum R juga bergerak. Jika panjang jarum
penunjuk R adalah H dan diameter dari silinder penunjuk adalah ha maka
perbesaran pada tahap ini adalah H/h. Seandainya panjang lengan Y adalah
L dan bergeraknya blok M adalah x maka perbesaran totalnya adalah L/X x
H/1/2h.
Perlu ditambahkan di sini bahwa penekan yang ujungnya runcing dapat
diatur jaraknya terhadap sumbu engsel dari blok M dan blok F dengan
mengubah-ubah ikatan baut pengatur yang terikat pada poros pengukur.
Pemasangan poros pengukur pada rumah ukur hanya menggunakan diafragma
saja, sehingga kerugian gesekan dapat diatasi.
- Pengubah Mekanis Optis
Dalam alat ukur pembanding ini digunakan sistem pengubah gabungan yaitu
pengubah mekanis dan pengubah optis. Pengubah mekanis berfungsi untuk
menghasilkan perubahan jarak karena persentuhan sensor dengan objek
ukur. Perubahan ini akan diperjelas melalui perbesaran optis. Pengubah
optis di sini bekerja menurut prinsip optik, yaitu dengan menggunakan
beberapa cermin atau lensa. Perubahan batang pengukur akan mengubah
posisi kemiringan dari cermin. Kemiringan posisi pemantul cahaya ini
mengakibatkan perubahan bayangan yang terjadi yang diproyeksikan ke
layar kaca yang berskala.
- Pengubah Elektris
Kini sudah banyak alat-alat ukur yang cara kerjanya menggunakan sistem
elektronik, di samping alat-alat ukur yang dioperasikan secara manual.
Prinsip kelistrikan yang digunakan dalam pengubah elektris ini mempunyai
fungsi untuk mengubah semua isyarat yang diterima oleh alat ukur
(besaran yang tidak bersifat elektris) menjadi suatu besaran yang
bersifat elektris. Dengan adanya prinsip kelistrikan maka besaran yang
bersifat kelistrikan tersebut diolah dan diubah menjadi lebih jelas
sehingga perubahan ini dapat dibaca pada skala alat ukur. Salah satu
contoh dari pengubah elektris ini adalah pengubah yang bekerjanya dengan
prinsip kapasitor.Timbulnya kapasitor karena adanya dua buah pelat
metal yang berpenampang sama diletakkan berdekatan dengan jarak l.
Besarnya kapasitas tergantung pada jarak l. Makin jauh jarak pelat maka
kapasitasnya akan menjadi turun, sebaliknya makin dekat jarak pelat
kapasitasnya makin naik. Bila silinder sensor menyentuh objek ukur tentu
terjadi perubahan jarak antara pelat metal karena diubah oleh silinder
tadi. Prinsip perubahan inilah yang digunakan oleh alat-alat ukur yang
mempunyai pengubah mengikuti sistem elektris.
- Pengubah Optis
Dalam ilmu fisika dipelajari masalah optis dengan hukum-hukumnya.
Prinsip-prinsip dalam optis inilah yang digunakan oleh alat-alat ukur
yang mempunyai pengubah optis. Sebetulnya sistem optis di sini hanya
berfungsi untuk membelokkan berkas cahaya dari objek ukur sehingga
terjadi bayangan maya atau nyata yang ukurannya bisa menjadi lebih besar
dari pada objek ukurnya. Dalam sistem optis kebanyakan menggunakan
bermacam-macam lensa seperti cermin datar, lensa cekung dan cembung,
lensa prisma, dan sebagainya. Contoh dari alat-alat ukur yang
menggunakan pengubah sistem optis ini adalah: kaca pembesar, mikroskop,
proyektor, teleskop, autokolimator, dan teleskop posisi.
- Kaca Pembesar
Dengan alat ini seseorang dapat melihat langsung suatu objek yang
diletakkan tepat pada fokusnya di mana yang dilihat mempunyai ukuran
yang lebih besar dari pada objek sesungguhnya.
- Mikroskop
Penggabungan dua buah lensa pembesar menjadi satu sistem optis biasa
disebut dengan mikroskop. Dengan demikian terdapat dua lensa yang
berbeda, namanya, ada yang disebut dengan okuler (dekat dengan mata) dan
ada yang disebut dengan objektif (dekat objek ukur).
- Proyektor
Seperti halnya pada mikroskop, pada proyektor pun terdapat kombinasi
sistem lensa yaitu lensa kondensor dan proyeksi. Tidak semua objek ukur
mempunyai sifat tembus cahaya. Dengan bantuan sinar yang lewat melalui
kondensor maka berkas cahayanya akan menyinari benda ukur yang
diletakkan di antara kondensor dan proyeksi. Benda ukur yang tidak
tembus cahaya ini akan menimbulkan bayangan yang gelap tapi latar
belakangnya terang. Pemeriksaan bayangan dari benda ukur dilakukan di
balik layar yang terbuat dari kaca buram.
- Teleskop
Salah satu alat ukur optis yang dapat digunakan untuk melihat objek ukur
yang relatif jauh letaknya yaitu yang biasa disebut dengan teleskop.
Pada alat ini juga digunakan dua lensa yaitu okuler dan objektif.
Bayangan atau berkas cahaya yang jauh difokuskan oleh objektif tepat
pada fokusnya okuler. Dengan adanya lensa okuler maka bayangan sebagai
hasil pembiasan objektif akan dibiaskan menjadi bayangan atau berkas
yang sejajar. Hal ini menyebabkan bayangan dari objek ukur menjadi lebih
jelas dilihat oleh mata.
- Autokolimator
Autokolimator merupakan alat ukur optis yang menggunakan prinsip dasar
dari teleskop. Kondensor di sini membuat berkas cahaya menjadi searah
menuju ke suatu target yang berbentuk garis. Sebuah cermin semi
reflektor yang kemiringannya 45 terhadap sumbu optis akan membuat target
terletak pada sumbu optis dan tepat pada fokus objektif. Objektif di
sini sering juga disebut dengan kolimator. Lensa objektif ini
menyebabkan berkas yang keluar menjadi sejajar. Berkas yang sejajar ini
dipantulkan kembali oleh cermin yang terletak pada jarak tertentu di
depan autokolimator. Bila posisi cermin dimiringkan sedikit maka berkas
cahaya diterima kembali oleh objektif, lalu difokuskan pada bidang fokus
namun letaknya tidak tepat pada sumbu optis.Pada bagian okuler
dilengkapi pula dengan mikrometer yang gunanya untuk mengetahui besarnya
perubahan posisi. Dengan alat autokolimator ini bisa diperoleh hasil
pengukuran dengan kemiringan maksimum 10 menit. Sedangkan kecermatan
dari skala alat ukur optis ini adalah 0,1 detik. Perubahan posisi cermin
terjadi karena ada perubahan posisi dari benda ukur.
- Pengubah Pneumatis
Kondisi aliran udara yang tertentu akan berubah bila area di mana udara
itu lalu juga berubah (menjadi lebih sempit atau lebih luas). Prinsip
inilah yang digunakan dalam alat ukur yang memakai pengubah sistem
pneumatis. Jadi, pada sistem pneumatis kondisi aliran udara akan berubah
bila celah antara objek ukur dengan sensor alat ukur di mana udara lalu
juga mengalami perubahan. Untuk mengetahui perubahan ini digunakan cara
yaitu pengukur perubahan tekanan dan kecepatan aliran udara. Dalam
pengubah sistem pneumatis paling tidak terdapat tiga komponen yaitu:
- sumber udara tekan
- sensor sekaligus sebagai pengubah
- pengukur perubahan aliran udara
Ada dua macam sistem pengubah pneumatis yang biasa digunakan yaitu:
- sistem tekanan balik (back pressure system)
- sistem kecepatan aliran (flow velocity system)
Penunjuk atau Pencatat
Hampir semua alat ukur mempunyai bagian yang disebut dengan penunjuk
atau pencatat kecuali beberapa alat ukur batas atau standar. Dari bagian
penunjuk inilah dapat dibaca atau diketahui besarnya harga hasil
pengukuran. Secara umum, penunjuk/pencatat ini dapat dikelompokkan
menjadi dua yaitu:
- Penunjuk yang mempunyai skala
- Penunjuk berangka (sistem digital)
Penunjuk yang Mempunyai Skala
Susunan garis-garis yang dibuat secara teratur dengan jarak garis yang
tetap serta tiap garis mempunyai arti tertentu biasanya disebut dengan
skala. Pada alat ukur panjang satu meter misalnya, jarak antara dua
garis atau jarak antara garis-garis menunjukkan bagian-bagian dari satu
meter. Demikian juga untuk alat-alat ukur yang lain misalnya derajat
untuk sudut. Dalam pembacaan skala biasanya dibantu dengan garis indeks
atau jarum penunjuk yang bergeser secara relatif terhadap skala. Dengan
memerhatikan posisi dari garis indeks dan jarum penunjuk maka diketahui
berapa besar dimensi dari objek yang diukur.
Kadang-kadang untuk skala-skala ukur tertentu tidak bisa dibaca langsung
ukurannya karena masih harus dikalikan dengan bilangan tertentu sesuai
dengan ketelitian alat ukurnya. Kadang-kadang posisi garis indeks tidak
selalu tepat dengan garis skala ukur sehingga hal ini sering menimbulkan
perkiraan dalam pembacaannya. Untuk mengurangi sistem perkiraan dalam
membaca skala maka dibuat skala nonius sebagai pengganti garis indeks.
Ada dua macam skala nonius yaitu skala nonius satu dimensi dan skala
nonius dua dimensi.
Untuk penunjuk berangka tidak terlalu sulit menggunakannya karena hasil
pengukuran dapat langsung dibaca pada penunjuknya yang secara otomatis
menunjukkan besarnya dimensi objek ukur. Penunjuk berangka ini ada yang
bekerjanya secara mekanis dan ada pula yang secara elektronik. Penunjuk
berangka secara mekanis misalnya pada jangka sorong dan mikrometer yang
memang dilengkapi dengan penunjuk berangka. Sedang penunjuk berangka
secara elektrik banyak dijumpai pada alat-alat ukur yang mempunyai
pengubah elektris. Sekarang banyak mesin-mesin produksi yang bekerjanya
dengan sistem komputer sehingga semua dimensi ukuran dari benda kerja
dapat dimonitor secara langsung. Penunjuk berangka sering juga disebut
dengan penunjuk digital.
Pencatat merupakan penunjuk juga, akan tetapi hasil pengukurannya
digambarkan dalam bentuk grafik pada kertas yang berskala. Untuk
pengukuran kekasaran permukaan ataupun kebulatan suatu poros banyak
digunakan pencatat. Sebagian besar pencatat ini bekerja secara elektris.
Klasifikasi Pengukuran
Geometris objek ukur mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Oleh karena
itu caranya mengukur pun bisa bermacam-macam. Agar hasil pengukurannya
mendapatkan hasil yang paling baik menurut standar yang berlaku maka
diperlukan cara pengukuran yang tepat dan benar. Untuk itu perlu juga
diketahui klasifikasi dari pengukuran. Ada beberapa cara pengukuran yang
bisa dilakukan untuk mengukur geometris objek ukur yaitu:
- Pengukuran Langsung
Proses pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca langsung dari
alat ukur yang digunakan disebut dengan pengukuran langsung. Misalnya
mengukur diameter poros dengan jangka sorong atau mikrometer.
- Pengukuran Tak Langsung
Bila dalam proses pengukuran tidak bisa digunakan satu alat ukur saja
dan tidak bisa dibaca langsung hasil pengukurannya maka pengukuran yang
demikian ini disebut dengan pengukuran tak langsung. Kadang-kadang untuk
mengukur satu benda ukur diperlukan dua atau tiga alat ukur, biasanya
ada alat ukur standar, alat ukur pembanding dan alat ukur pembantu.
Misalnya mengukur ketirusan poros dengan menggunakan senter sinus (sine center) yang harus dibantu dengan jam ukur (dial indicator) dan blok ukur.
- Pengukuran dengan Kaliber Batas
Kadang-kadang dalam proses pengukuran kita perlu melihat berapa besar
ukuran benda yang dibuat melainkan hanya untuk melihat apakah benda yang
dibuat masih dalam batas-batas toleransi tertentu. Misalnya saja
mengukur diameter lubang. Dengan menggunakan alat ukur jenis kaliber
batas dapat ditentukan apakah benda yang dibuat masuk dalam kategori
diterima (Go) atau masuk dalam kategori dibuang atau ditolak (No Go). Dengan demikian sudah tentu alat yang digunakan untuk pengecekannya adalah kaliber batas Go dan No Go.
Pengukuran seperti ini disebut pengukuran dengan kaliber batas.
Keputusan yang diambil adalah: dimensi objek ukur yang masih dalam batas
toleransi dianggap baik dan dipakai, sedang dimensi yang terletak di
luar batas toleransi dianggap jelek. Pengukuran cara ini tepat sekali
untuk pengukuran dalam jumlah banyak dan membutuhkan waktu yang cepat.
- Pengukuran dengan Bentuk Standar
Pengukuran disini sifatnya hanya membandingkan bentuk benda yang dibuat
dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat pembanding.
Misalnya kita akan mengecek sudut ulir atau roda gigi, mengecek sudut
tirus dari poros kronis, mengecek radius dan sebagainya. Pengukuran
dilakukan dengan alat ukur proyeksi. Jadi, di sini sifatnya tidak
membaca besarnya ukuran tetapi mencocokkan bentuk aja. Misalnya sudut
ulir dicek dengan mal ulir atau alat pengecek ulir lainnya.
Klasifikasi Alat Ukur
Geometris objek ukur mempunyai bentuk dan ukuran yang bervariasi. Adanya
variasi bentuk dan ukuran inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai
jenis alat ukur dan jenis pengukuran. Untuk jenis pengukuran sudah
dibicarakan di atas, jenis alat ukur perlu juga dibicarakan yang
dititikberatkan pada sifat alat ukur itu sendiri maupun pada jenis benda
yang diukur.
Menurut cara kerja dari alat ukur maka alat ukur dapat diklasifikasikan
sebagai berikut: alat ukur mekanis, alat ukur elektris, alat ukur optis,
alat ukur mekanis optis dan alat ukur pneumatis. Ini semua sudah
dibicarakan pada bagian pengubah alat ukur.
Menurut sifat dari alat ukur maka alat ukur dapat dibedakan menjadi:
- Alat ukur langsung, hasil pengukurannya dapat langsung dapat dibaca
pada skala ukurnya. Misalnya jangka sorong, mikrometer dan sebagainya.
- Alat ukur pembanding, alat ukur yang mempunyai skala ukur yang telah
dikalibrasi. Dipakai sebagai pembanding alat ukur yang lain. Misalnya:
jam ukur (dial indicator), pembanding (comparator).
- Alat ukur standar, alat ukur yang mempunyai harga ukuran tertentu.
Biasanya digunakan bersama-sama dengan alat ukur pembanding misalnya:
blok ukur (gauge block), batang ukur (length bar) dan master ketinggian (height master).
- Alat ukur batas, alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah
suatu dimensi objek ukur masih terletak dalam batas-batas toleransi
ukuran. Misalnya: kaliber-kaliber batas Go dan No Go.
- Alat ukur bantu, alat ukur yang sifatnya hanya sebagai pembantu
dalam proses pengukuran. Misalnya: dudukan mikrometer,
penyangga/pemegang jam ukur, dan sebagainya.
Menurut jenis dari benda yang akan diukur maka alat ukur dapat pula diklasifikasikan menjadi:
- Alat ukur-alat ukur linier, baik alat ukur linier langsung maupun alat ukur linier tak langsung.
- Alat ukur sudut atau kemiringan. Ada alat ukur sudut yang langsung
bisa dibaca skala sudutnya ada juga yang harus menggunakan perhitungan
secara matematika.
- Alat ukur kedataran.
- Alat ukur untuk mengukur profil atau bentuk.
- Alat ukur ulir.
- Alat ukur roda gigi.
- Alat ukur mengecek kekasaran permukaan.
Sifat Umum Alat Ukur
Bagaimanapun baiknya atau sempurnanya suatu alat ukur tentu ada
kekurangan-kekurangannya. Karena memang disadari bahwa alat ukur adalah
buatan manusia. Kesempurnaan buatan manusia ada batasnya. Oleh karena
itu, bila ada kekurang tepatan dari alat ukur harus kita maklumi karena
hal itu memang merupakan sifat dari alat ukur. Untuk itu perlu juga
dipelajari masalah sifat-sifat dari alat ukur. Dalam istilah keteknikan
ada beberapa sifat dari alat ukur yang perlu diketahui yaitu:
rantai kalibrasi, kepekaan, kemudahan baca, histerisis, kepasifan, kestabilan nol dan pengambangan.
Rantai Kalibrasi
Kadang-kadang alat-alat ukur yang habis dipakai harus dicek kembali
ketepatannya dengan membandingkannya pada alat ukur standar. Proses
seperti ini biasa disebut dengan istilah kalibrasi. Kalibrasi adalah
mencocokkan harga-harga yang ada pada skala ukur dengan harga-harga
standar atau harga sebenarnya. Sebetulnya, kalibrasi ini tidak saja
dilakukan pada alat-alat ukur yang sudah lama atau habis dipakai, tetapi
juga untuk alat-alat ukur yang baru dibuat. Pemeriksaan alat-alat ukur
standar panjang dapat dilakukan melalui rangkaian sebagai berikut:
Tingkat 1: Pada tingkat ini kalibrasi untuk alat ukur kerja dengan alat ukur standar kerja.
Tingkat 2: Pada tingkatan yang kedua, kalibrasi dilakukan untuk alat ukur standar kerja terhadap alat ukur standar.
Tingkat 3: Pada tingkat yang ketiga, dilakukan kalibrasi alat ukur
standar dengan alat ukur standar yang mempunyai tingkatan yang lebih
tinggi, misalnya standar nasional.
Tingkat 4: Pada tingkat terakhir ini, dilakukan kalibrasi standar nasional dengan standar meter internasional.
Dengan urut-urutan kalibrasi di atas maka dapat dijamin bahwa alat-alat
ukur panjang masih tetap tepat dan teliti untuk digunakan dalam bengkel
kerja. Di samping itu, dengan adanya rantai kalibrasi di atas dapat
dihindari terjadinya pemeriksaan langsung alat ukur standar kerja dengan
standar meter internasional.
Kepekaan (Sentivity)
Kepekaan alat ukur menyangkut masalah kemampuan dari alat ukur untuk
memonitor perbedaan yang kecil dari harga-harga yang diukur. Kepekaan
suatu alat ukur berkaitan erat dengan sistem mekanisme dari pengubahnya.
Makin teliti sistem pengubah mengolah isyarat dari sensor maka makin
peka pula alat ukurnya.
Kemudahan Baca (Readability)
Kalau kepekaan berkaitan erat dengan sistem pengubah maka kemudahan baca
berkaitan erat dengan sistem skala yang dibuat. Jadi, kemampuan alat
ukur untuk menunjukkan harga yang jelas pada skala ukurnya dapat
diartikan sebagai kemudahan baca alat ukur tersebut. Di sini, pembuatan
skala nonius dengan sistem yang lebih terperinci memegang peranan
penting dalam masalah kemudahan baca. Akhir-akhir ini sistem penunjuk
digital secara elektronis banyak digunakan dalam rangka mencari
kemudahan baca yang tinggi.
Histerisis
Pada waktu dilakukan pengukuran sudut benda kerja di atas batang sinus (
sine bar) atau dengan senter sinus (
sine center) dengan menggunakan alat ukur pembanding jam ukur (
dial indicator)
biasanya dilakukan pengukuran bolak-balik. Bolak-balik di sini artinya
jam ukur digerakkan dalam dua arah yaitu dari titik terendah menuju
titik tertinggi dari benda ukur, dan dari titik tertinggi menuju ke
titik terendah. Kalau
diperhatikan pengukuran pada waktu menuju ke titik tertinggi dan kembali
ke titik terendah kadang-kadang didapatkan penyimpangan. Penyimpangan
yang terjadi sewaktu dilakukan pengukuran dari titik terendah (titik
nol) sampai titik tertinggi (maksimum) kemudian kembali lagi dari titik
tertinggi sampai ke titik terendah disebut dengan histerisis.
Perbedaan tersebut timbul karena pada waktu poros jam ukur bergerak ke
atas banyak gaya-gaya yang harus dilawannya seperti gaya pegas dan gaya
gesek, pada waktu poros jam ukur turun gaya pegas malah mendorongnya
tetapi gaya gesekan harus dilawannya. Untuk menghindari histerisis maka
gesekan poros dengan bantalannya harus dibuat seminimum mungkin.
Kalaupun ada pengaruh histerisis, pengaruh ini dapat dikurangi dengan
jalan membuat tinggi susunan blok ukur kira-kira sama dengan tinggi
benda ukur, sehingga dengan demikian perbedaan ukuran yang ditunjukkan
oleh jam ukur adalah relatif kecil.
Kepasifan
Kadang-kadang sewaktu dilakukan pengukuran terjadi pula bahwa jarum
penunjuk skala tidak bergerak sama sekali pada waktu terjadi perbedaan
harga yang kecil. Atau dapat dikatakan isyarat yang kecil dari sensor
alat ukur tidak menimbulkan perubahan sama sekali pada jarum
penunjuknya. Keadaan yang demikian inilah yang sering disebut dengan
kepasifan atau kelambatan gerak alat ukur.
Untuk alat-alat ukur mekanis kalaupun terjadi kepasifan atau kelambatan
gerak jarum penunjuknya mungkin disebabkan oleh pengaruh pegas yang
sifat elastisnya kurang sempurnya. Pada alat ukur pneumatis juga sering
terjadi kepasifan ini misalnya lambatnya reaksi dari barometer padahal
sudah terjadi perubahan tekanan udara. Hal ini disebabkan volume
udaranya terlalu besar akibat dari terlalu panjangnya pipa penghubung
sensor dengan ruang perantara.
Pergeseran (Shifting)
Pergeseran adalah penyimpangan yang terjadi dari harga-harga yang
ditunjukkan pada skala atau yang tercatat pada kertas grafik padahal
sensor tidak melakukan perubahan apa-apa. Kejadian seperti ini sering
disebut dengan istilah pergeseran, banyak terjadi pada alat-alat ukur
elektris yang komponen-komponennya sudah tua.
Pengambangan (Floating)
Kadang-kadang terjadi pula jarum penunjuk dari alat ukur yang digunakan
posisinya berubah-ubah. Atau kalau penunjuknya dengan sistem digital
angka paling kanan atau angka terakhir berubah-ubah. Kejadian seperti
ini dinamakan pengambangan. Kepekaan dari alat ukur akan membuat
perubahan kecil dari sensor diperbesar oleh pengubah.
Makin peka alat ukur makin besar pula kemungkinan terjadinya
pengambangan. Untuk itu, bila menggunakan alat-alat ukur yang mempunyai
jarum penunjuk pada skalanya atau penunjuk digital harus dihindari
adanya kotoran atau getaran, juga harus digunakan metode pengukuran yang
secermat mungkin.
Kestabilan Nol (Zero Stability)
Pada waktu mengukur dengan jam ukur, kemudian secara tiba-tiba diambil
benda ukurnya, maka seharusnya jarum penunjuk kembali pada posisi nol
semula. Akan tetapi, sering terjadi bahwa jarum penunjuknya tidak
kembali ke posisi nol. Keadaan ini disebut dengan kestabilan nol yang
tidak baik. Salah satu penyebab tidak kembalinya pada posisi nol adalah
adanya keausan pada sistem penggerak jarum penunjuk.
Dengan demikian jelaslah bahwa banyak sekali hal-hal yang dapat
menimbulkan penyimpangan dalam pengukuran yang salah satunya disebabkan
oleh sifat-sifat dari alat ukur itu sendiri. Oleh karena itu, untuk
mengurangi banyaknya penyimpangan perlu dilakukan pengecekan alat-alat
ukur, baik yang belum digunakan lebih-lebih lagi untuk alat-alat ukur
yang sering digunakan. Jadi, kalibrasi alat ukur memang sangat
diperlukan, disamping untuk mengecek sifat-sifat dari alat ukur. Kalau
hal yang demikian ini dilakukan secara rutin maka penyimpangan
pengukuran yang timbul dari alat ukur bisa dikurangi menjadi sekecil
mungkin.
Ada beberapa istilah dan definisi dalam pengukuran yang harus dipahami, diantaranya:
- Akurasi, kedekatan alat ukur membaca pada nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur.
- Presisi, hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran, atau derajat untuk membedakan satu pengukuran dengan lainnya.
- Kepekaan, rasio dari sinyal output atau tanggapan alat ukur perubahan input atau variabel yang diukur.
- Resolusi, perubahan terkecil dari nilai pengukuran yang mampu ditanggapi oleh alat ukur.
- Kesalahan, angka penyimpangan dari nilai sebenarnya variabel yang diukur.